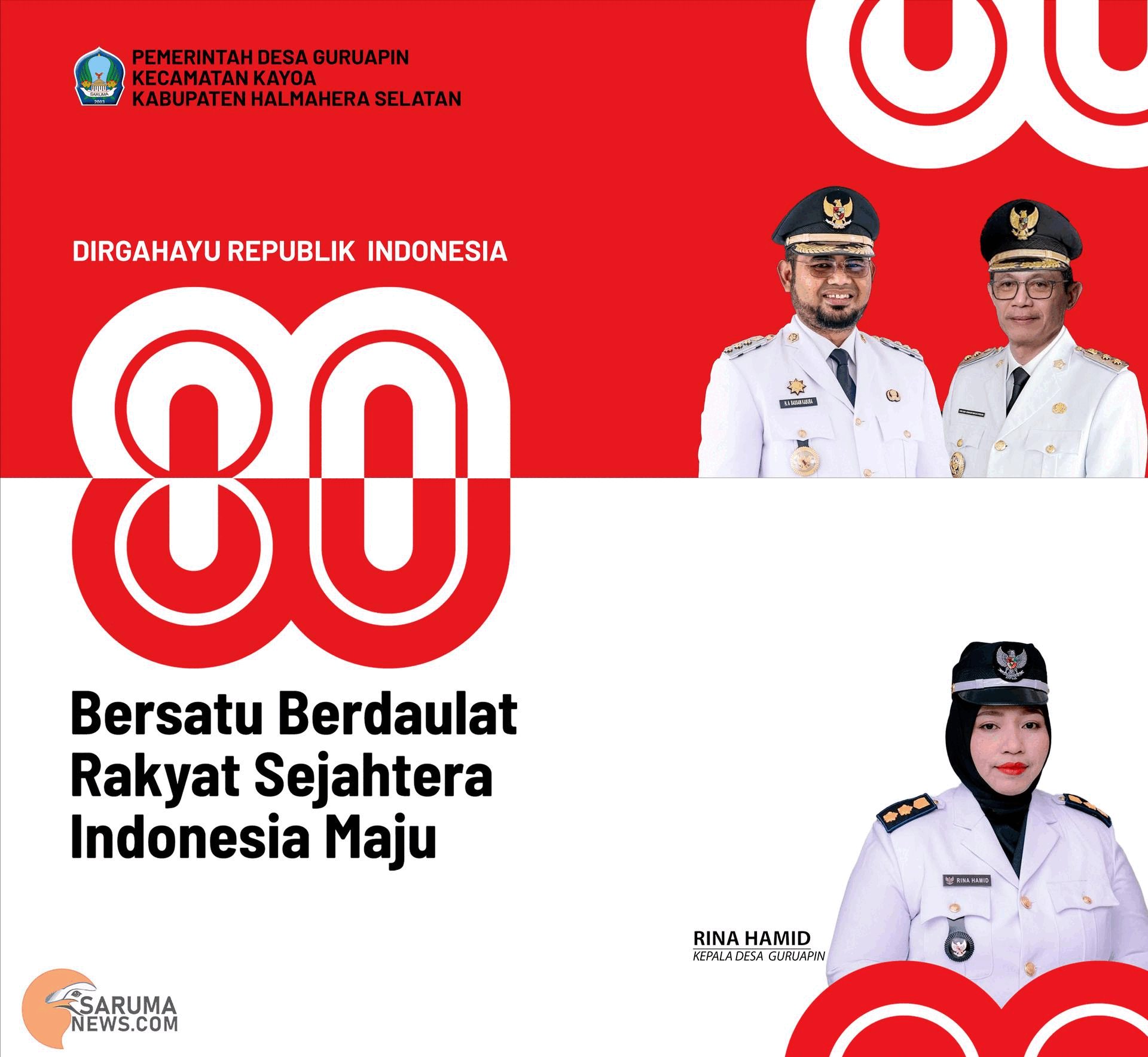PAGAR

“Seluruh halaman ditutupi dengan pagar anyaman tinggi, tak dapat dilihat dari jalanan. Apa sebab dipagar rapat tinggi? Agar orang tak tahu apa yang terjadi di dalam…”
Saya membayangkan Pramoedya Ananta Toer menuliskan ini sambil mengenang goyangan pucuk pohon kayu putih yang rimbun di pulau Buru. Di pulau ini Ia “ditahan” dan menjalani ketidakbebasan secara fisik. Namun pikirannya bergerilya. Menentang semua kekejian dengan tulisan-tulisan yang membebaskan. Kalimat pembuka di atas saya petik dari novel Pram, “Perawan Dalam Cengkeraman Militer” – yang memotret dengan pias kisah perbudakan seks di zaman Jepang. Sebuah kisah yang suram saat perempuan Indonesia dijadikan pemuas nafsu tentara. Jepang tak mencatat “kebiadaban” ini dalam buku sejarahnya sehingga nasib perempuan-perempuan itu terkurung dalam nista yang sunyi.
“Seluruh halaman” menunjuk teritori. Ada batas kuasa di sana. Dan pagar jadi yang “mewakili” batas itu. “Apa sebab dipagar tinggi?. Ada kausalitas antara kesadaran untuk membuat pagar dan tujuan untuk melindungi yang terpagar. Halaman yang dipagar bisa jadi sebuah rumah, sebuah pemondokan atau sebuah kompleks tempat nista itu dilakukan. Ada enigma yang disembulkan. Sengaja menyembunyikan yang terjadi di dalam agar orang ramai tak tahu. Dan orang ramai akan bertanya apa yang terjadi di dalam sana?. Pagar dari anyaman yang tinggi sebagaimana “kesaksian” Pram tak hanya jadi pemisah untuk netra tapi juga untuk hasrat mengetahui. Dan yang di dalam menjadi “terlindungi” sekaligus mungkin terampas kebebasannya.
Pagar adalah adaptasi paling awal yang dilakukan manusia kala peradabannya terancam. Yuval Noah Harari dalam “Sapiens” menyebut, agar survive dalam piramida rantai makanan yang riuh dengan saling berebut dan membinasakan, homo sapiens menciptakan api. Tujuannya untuk menghangatkan tubuh dan menjadi “pagar” dari ancaman binatang buas. Dengan api manusia berevolusi untuk menguasai. Henri Bergson, filsuf Perancis yang mengikuti pandangan Darwin menyebut “ada” berarti “berubah”. Yang berubah itu menunjukan eksistensi. Sesuatu yang dinamis. Ada upaya bertahan hidup lebih lama dengan cara “berubah” sehingga tetap “ada”.
Seminggu lalu, saya terlibat diskusi dengan seorang jurnalis sekaligus penulis muda yang suka “memotret” ketidaklaziman. Namanya Faris Bobero. Ia baru pulang menjelajah sebuah gugusan kepulauan nan eskotis yang berserak tepat dibawah poros vertikal khatulistiwa. Di Kayoa – nama gugusan pulau itu – pantai dan air laut transparan dengan terumbu karang dan ikan berbagai jenis adalah keindahan yang tak tepermanai. Banyak foto yang diperlihatkan Faris sepanjang kami berdiskusi. Semuanya mengalir seperti biasa hingga Ia menunjukan beberapa foto pemukiman warga yang menurut saya terlihat “unik”.
Di foto-foto itu, pagar beton dengan warna yang mencolok mendominasi landskap dengan latar rumah warga yang sederhana. Berdinding tembok dari campuran kapur dan semen dengan cat putih yang mulai pucat. Jendelanya ompong tanpa sekat. Di kiri kanan rumah itu, berjejajal banyak rumah yang hanya memperlihatkan tatakan batu bata pada dindingnya yang telanjang. Ada pula yang setengah tembok setengah papan. Terlihat kontras. Jalanan pemukiman yang tak beraspal membuat pagar beton itu makin terasing. Di beberapa pemukiman yang lain, entah di desa atau di kota, fenomena yang sama juga terekam mata. Saya tak tahu apakah ini bagian dari cara “berubah” sehingga tetap “ada” sebagaimana pendapat Darwin atau peradaban tengah berjalan menuju modernitas meski dengan langkah yang goyah.
Semasa kecil, membuat pagar dari bambu yang dibelah dan kayu hasil gergajian adalah rutinitas yang guyub. Entah sebagai batas kebun atau penanda halaman rumah. Ada interaksi sosial setiap pagar akan dibuat. Warga saling membantu karena pagar tak memisahkan relasi kemanusiaan. Ada percakapan yang saling menautkan. Dulu itu, hewan peliharaan atau yang tanpa pemilik masih bebas berkeliaran. Kota belum tumbuh genit. Jarak antara rumah masih menyisakan banyak ruang kosong. Dan karena itu, pagar dibuatkan untuk melindungi tanpa memutus relasi dengan sesama.
Ketika kota bergeliat maju, pagar tetap dibangun dan jadi pembatas. Tetapi fungsinya mulai bergeser. Desainnya juga berubah mengikuti kemajuan peradaban. Bambu dan kayu berganti beton dan besi. Pemukiman jadi tak berjarak. Jika dulu tinggi pagar hanya sebatas untuk memastikan hewan tak menerobos, kini tingginya lebih menjulang. Kokoh dan berdiri dengan angkuh. Untuk apa pagar tinggi itu?. Agar manusia tak saling menerobos. Tak saling menyapa. Kemanusiaan meredup dan kehilangan empati. Pagar juga jadi simbol status sosial dan ekonomi. Di kota-kota yang terus melaju, pagar ibarat etalase yang “menjual” hedonisme pemiliknya.
Tak jarang pagar juga mewakili kepentingan politik. Bila musim kampanye tiba, akan datang para “calon wakil” yang menawarkan banyak hadiah. Jika terpilih, akan ada perbaikan. Yang paling mencolok adalah warna pagar – yang baru dibangun atau sudah ada sebelumnya. Jika partai biru menang, warna pagar akan membiru. Jika merah yang sukses, pagar akan memerah. Begitu juga kuning dan hijau atau gabungan beberapa warna. Pagar-pagar yang dicat itu seolah mewakili pilihan “yang di dalam”. Menjadi penanda sekaligus hegemoni politik. Pagar jadi tempat menaruh harapan. Juga Utopia. “Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, anda bisa bertaruh bahwa semuanya telah direncanakan”, kata Franklin D, Roosevelt.
Yang telah direncanakan itu pasti punya tujuan. Pagar saat ini berbentuk beleid yang memaksa. Di masa pandemi, pagar itu berupa sertifikat vaksin atau hasil test PCR. Mau bepergian, beribadah, makan, masuk mal, bersekolah, bekerja di kantor atau perusahaan – semuanya harus menunjukan sertifikat itu. Jika tidak maka anda akan jadi “musuh bersama”. Dianggap tak patuh dan sudah pasti terkucil. Anda berada di luar pagar karena akan mengancam “mereka” yang di dalam. Sertifikat vaksin dan hasil PCR telah menjadi “mata uang” kesehatan.
Padahal kita sungguh paham vaksin bukan obat mujarab untuk melawan coronavirus. Ia hanya membuat tubuh punya bonus senjata untuk melawan virus. Membentengi diri dari ancaman penyakit penyerta yang lain. Apakah kita punya pilihan lain?. Sementara ini tak ada. Vaksin jadi salah satu yang dianjurkan. Meski vaksin tak membuat kebal. Ia berbeda dengan imunisasi saat kita balita. Sekali seumur hidup. Yang berbeda itu karena mungkin dulu hanya ada satu “merek” dan dipakai secara universal. Saat ini banyak merek dan terserah pilihannya.
Perkara memilih bukan sesuatu yang enteng. Memilih itu subyektif. Selalu menghitung untung-rugi. Mengkalkulasi semua kemungkinan. Kadang terjebak dalam tekanan politik, sosial dan ekonomi. Dan ketika pilihan sudah diambil, yang tersisa hanya dua muara yang terpisah ; kepuasan atau penyesalan. Peradaban sering memilih jalan yang benar meski kerap kali terantuk kecemasan saat berada di jalan yang salah. Kita diberi opsi damai tapi lebih suka berperang. Diminta berhenti menjadi kurir yang menyebarkan virus, kita malah sibuk berkerumun. Kemanusiaan selalu merasa jadi penguasa tunggal yang suka mengatur. Sang pemenang yang gemar merusak alam dan menyingkirkan spesies yang lain. Kita sibuk membangun pagar yang membungkam kekerabatan sosial sambil merayakan kebebasan. Meski juga selalu cemas.
Ada bias kognitif yang tak berujung. Tiap bias mendistorsi persepsi kita tentang masa depan kemanusiaan. Edward Osborne Wilson, ahli sosiobiologi Amerika menyebut, kita tengah berada dalam era Eremosen. Zaman kesendirian.
**Asgar Saleh**