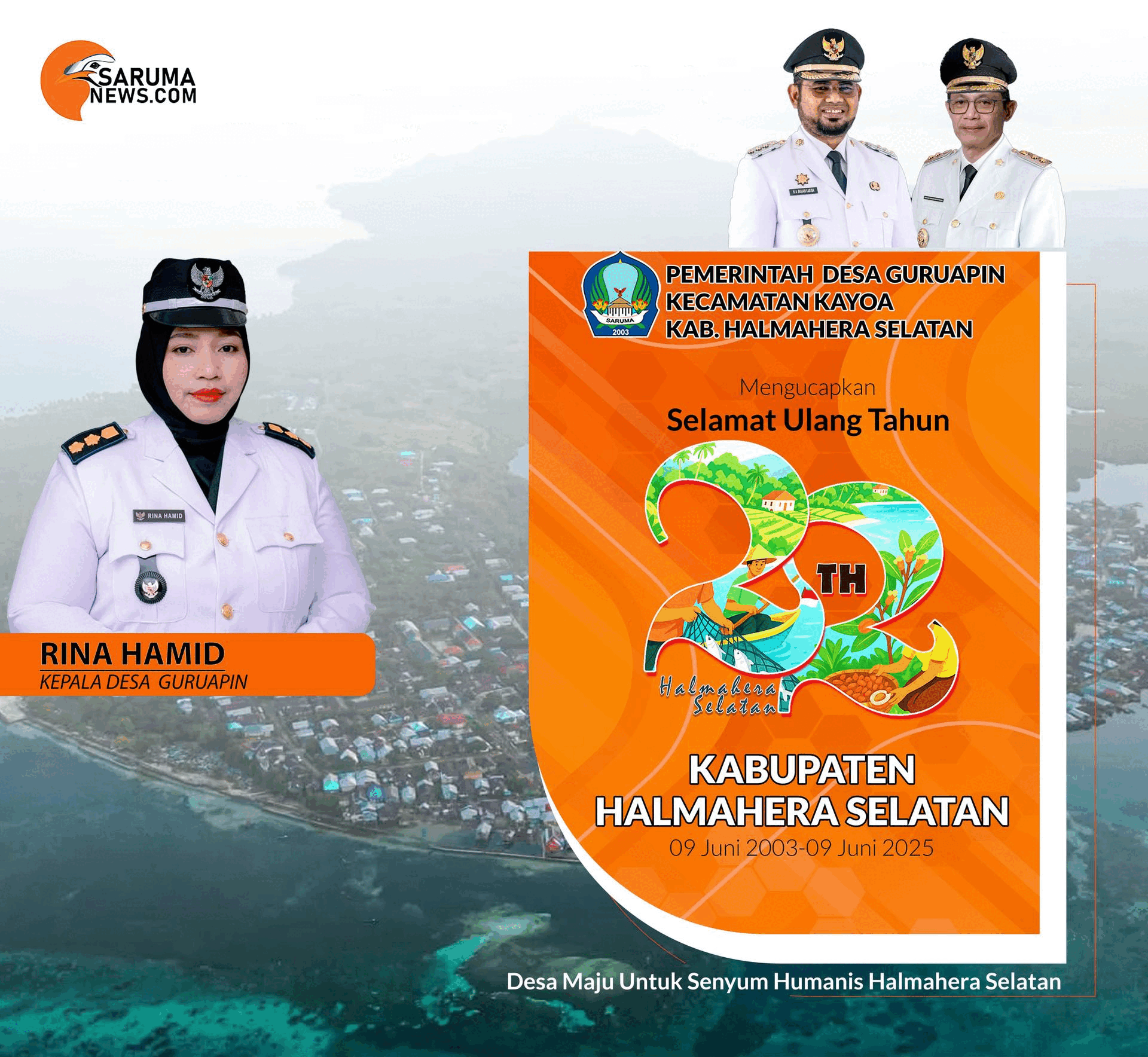Aktifis Alumni Makassar
Hanyalah sebuah majas judul diatas, Sebenarnya menjelaskan seorang pemimpin yang suka merespon informasi buruk tentangnya dan sulit menerima masukan baik dari orang sekelilingnya, ia juga sering tak sadar diri kalau kebijakannya selalu timpang (Diskresi).
Tipologi pejabat seperti ini persis dengan tulisan George Orwell tentang omongan baru dalam wacana politik (Newspeak) “manusia si pentol korek” ada kepala namun tak punya otak, gesek sedikit langsung terbakar. Tindakan represif adalah jalan utama sementara persuasif selalu tak ada jalannya.
Jika melihat dan tinggal di lingkungan pejabat seperti ini, saya seolah gregetan, semacam posesiflah, pokoknya ingin dekat dan pengen cubit ginjal si pejabat itu.
Tipikal lainnya, ia selalu beralibi kalau salah, suka menghindar serta tak mau berdialog jika gelombang demonstran datang pertanyakan kinerjanya. Parahnya bukan mendengar keluh kesah justru menghadang mereka yang menentang dengan preman peliharaannnya.
Bukanlah fenomena langkah ciri pejabat seperti ini, demikianlah adanya semenjak pasca reformasi, mental pejabat orde baru diwarisi secara sempurna di abad sekarang ini. Desentralisasi memang telah tercapai sesuai tuntunan aktivis 98, namun jauh dari cita-citanya. Justru malah melahirkan raja-raja kecil, bermunculan angkuhnya karena alasan kewenangan UU Otoda.
Salah satu penelitian bersumber dari jurnal terindeks (Neffinegger, 1989) semakin kebawah (kecil) suatu wilayah yang dipimpin seseorang maka semakin tinggi pula keangkuhan pemimpin tersebut, apalagi latar belakang pemimpin itu dilandasi dengan pendidikan yang rendah.
Sejalan juga dengan kata Marzuki Ali (Ketua DPR RI 2009-2014) saat membuka acara pertemuan pemuda kawasan timur Indonesia 2012 di gedung Cut Nyiak Dien, di Jakarta siang itu. Saat itu saya hadir sebagai perwakilan Universitas 45 Makassar, menyimak betul apa yang ia sampaikan dalam pertemuan pemuda yang kami adakan.
“Bahwa tujuan reformasi telah disalah artikan, desentralisasi kini salah kaprah, pejabat daerah telah menjadi buas bagi rakyatnya, harus dilayani serta dihormati, tak mau mendengar hanya ingin didengar, keserakahan seolah terbentuk ketika jabatan itu mulai diemban”.
Sejatinya seperti inilah ketakutan Aktivis saat itu, satu sisi apapun konsekuensinya orde baru harus turun tahta namun disisi lain desentralisas justru akan membuka kran pejabat otoritarianisme.
Memonopoli kekuasaan serta merawat kembali tradisi korupsi kolusi dan nepotisme(KKN) di lingkungan pemerintah Daerah.
Biasanya kolega dan keluarganya sebagai representatif dari pejabat tersebut, menekan serta meneror akan nonjob/mutasi pegawai Daerah di tempat-tempat terluar jika kepentingan mereka tidak diakomodir.
Kartel jabatan dan pekerjaan daerah selalu terus dikomersilkan, Fit propertest (lelang jabatan), Lelang pekerjaan di LPSE hanyalah formalitas untuk mengelabui hukum. Pada konteks ini kolega dan keluarganya selalu menjadi peran utama.
Potret ini terus saja terulang dilingkungan pemerintahan Daerah, bahkan seolah telah menjadi tradisi setiap kali periode jabatan itu diemban. Bukan fenomena langka lagi namun telah menjadi budaya di lingkungan pemerintahan.
Dalam perspektif politik, hal demikian dibenarkan untuk merawat basis, sebab mereka berperan sebagai instrumen politik dan ekonomi untuk kepentingan di periode selanjutnya. Dasarnya karena kerja-kerja politik yang militan hanyalah ada pada keluarga dan koleganya. Namun menjadi Boomerang juga jika dasar kebijakannya tidak tepat sasaran, maka rusaknya pemerintahan akan berdampak pada reputasi dan popularitas pejabat tersebut.
Pada tahun-tahun politik berita kebaikan dan keburukan pejabat tersebut akan berseliweran di media-media sosial, kita sebagai followers akan diajak untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk memilih pemimpin di masa mendatang.
Saat tiba waktunya juga, kita perlu menyampaikan agar pejabat itu tau diri jika kinerjanya buruk, mengundurkan diri adalah solusinya sebelum dipersekusi dan dipermalukan di hari pemilihan tiba.